Menakar Amanat Reformasi : Cacat Proses Revisi UU TNI
OPINI

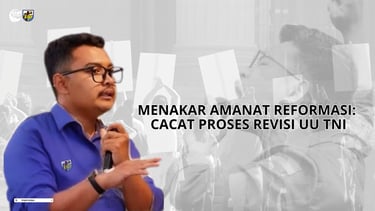
Kurun waktu lima tahun ke belakang, Indonesia merasakan gejolak penolakan yang besar terhadap kebijakan-kebijakan politik yang mencoba merombak sistem hukum di Indonesia melalui perubahan peraturan perundang-undangan. Pada 2019, gejolak penolakan terhadap perubahan UU KPK menjadi awal gelombang massa yang menyuarakan #ReformasiDikorupsi sebagai bentuk penolakan terhadap mufakat jahat untuk melemahkan KPK. Selanjutnya, kurun waktu 2020–2023, perjuangan menolak UU Cipta Kerja menjadi rangkaian panjang dalam upaya melawan pelemahan hak-hak pekerja serta jalan pintas untuk melanggengkan oligarki.
Hadirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 mengenai uji formil UU Cipta Kerja seharusnya menjadi alarm bagi pemerintah dan DPR RI untuk selalu mempertimbangkan setiap keputusan yang dibuat secara terburu-buru tanpa melibatkan masyarakat sebagai pewaris sah demokrasi Indonesia. Sejatinya, para pemangku jabatan yang memperoleh mandat dari pemilihan umum harus senantiasa kembali kepada masyarakat untuk mendengarkan serta mempertimbangkan setiap masukan yang diberikan. Sebab, pasca disahkannya UU KPK dan UU Cipta Kerja, pemerintah menghadapi pekerjaan rumah besar untuk kembali meraih kepercayaan publik dalam menjalankan kebijakan yang berdampak luas bagi masyarakat.
Memasuki awal 2025, masyarakat justru dikejutkan oleh gerak cepat pemerintah yang hendak segera membahas revisi UU TNI. Ironisnya, revisi ini tidak termasuk dalam target Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025, sementara draf naskah akademik serta RUU tidak dapat diakses oleh publik. Pembahasannya pun dilakukan secara tertutup di luar gedung parlemen. Perbuatan ini menunjukkan bahwa DPR RI dan pemerintah tidak belajar dari kesalahan dalam UU Cipta Kerja, yang secara legal formal telah menemui titik buntu di Mahkamah Konstitusi, tetapi akhirnya dipaksakan melalui Perppu sebagai jalan pintas untuk memenuhi ambisi kekuasaan. Maka, RUU TNI pun dilanggengkan dan disahkan dalam waktu singkat tanpa perlawanan sedikit pun di parlemen.
---
### PARTISIPASI PUBLIK YANG BERMAKNA (MEANINGFUL PARTICIPATION)
Mahkamah Konstitusi sebagai The Guardian of Constitution telah mengambil langkah tepat dengan mengeluarkan Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 mengenai uji formil UU Cipta Kerja. Keputusan ini seharusnya menjadi preseden bagi seluruh proses pembentukan peraturan perundang-undangan di berbagai tingkatan dan lembaga negara yang memiliki kewenangan dalam mengeluarkan produk hukum, sebagaimana diamanatkan dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Putusan tersebut menekankan tiga hal penting dalam mekanisme Meaningful Participation atau Partisipasi Publik yang Bermakna.
Dalam setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan—mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, hingga pengesahan dan pengundangan—partisipasi publik wajib diakomodasi. Bahkan, dalam perkembangannya, pemerintah yang memiliki kewenangan mengusulkan suatu undang-undang juga dapat berperan sebagai penyalur partisipasi publik. Oleh karena itu, tidak ada lagi alasan bagi pemerintah untuk mengabaikan keterlibatan masyarakat. Upaya Mahkamah Konstitusi ini merupakan langkah penertiban terhadap prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.
Menurut Maria Farida, dengan mengutip pendapat I.C. Van Der Vlies dan A. Hamid S. Attamimi, proses penyusunan peraturan perundang-undangan yang baik dibagi menjadi dua klasifikasi, yaitu asas formal dan asas material. Asas formal mencakup:
1. Asas tujuan yang jelas (*beginsel van duideleijke doelstelling*),
2. Asas organ/lembaga yang tepat (*beginsel van het juiste orgaan*),
3. Asas perlunya pengaturan (*het noodzakelijkheids beginsel*),
4. Asas dapatnya dilaksanakan (*het beginsel van uitvoerbaarheid*), dan
5. Asas konsensus (*het beginsel van consensus*).
Penerapan partisipasi publik bukan sekadar pelaksanaan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Mahkamah Konstitusi telah menegaskan bahwa pemangku kebijakan wajib menjamin tiga hak utama masyarakat dalam proses legislasi:
1. Hak untuk didengarkan pendapatnya (*right to be heard*),
2. Hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (*right to be considered*), dan
3. Hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (*right to be explained*).
Implementasi meaningful participation seharusnya bermuara pada kesejahteraan rakyat dengan mempertemukan kebutuhan masyarakat dan rancangan kebijakan yang disusun oleh pembentuk peraturan perundang-undangan. Namun, dalam praktiknya, pembentukan undang-undang sering kali dipengaruhi oleh kepentingan politik. Political bargaining (tawar-menawar politik) dalam legislasi kerap berujung pada kompromi yang kurang mencerminkan kepentingan publik.
---
### KETAATAN TERHADAP DEMOKRASI KONSTITUSIONAL
Penolakan terhadap revisi UU TNI mengingatkan kita pada amanat Reformasi 1998 sebagai tonggak perjuangan rakyat melawan otoritarianisme. Enam tuntutan Reformasi yang perlu diingat kembali adalah:
1. Menegakkan supremasi hukum,
2. Menghapus Dwifungsi ABRI,
3. Memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN),
4. Mengadili Soeharto dan kroninya,
5. Melakukan amandemen UUD NRI 1945, dan
6. Memberikan otonomi daerah seluas-luasnya.
Reformasi merupakan tonggak kebangkitan demokrasi di Indonesia. Namun, Reformasi juga menuntut adanya pembatasan kekuasaan agar kelembagaan negara tidak dibentuk secara sewenang-wenang. Selama 32 tahun berkuasa, Soeharto memanfaatkan konstitusi untuk melanggengkan otoritarianisme. Amandemen UUD NRI 1945 kemudian memangkas absolutisme itu dan membatasi masa jabatan.
Meminjam pemikiran Jürgen Habermas, demokrasi konstitusional adalah pertemuan antara supremasi hukum (*constitutionalism*) dan kehendak rakyat (*democracy*). Ketegangan antara dua elemen ini harus dinegosiasikan agar hukum dan politik dapat berjalan selaras. Saat ini, proses revisi UU TNI menunjukkan adanya kesenjangan besar antara pemerintah dan masyarakat, di mana tidak terjadi transfer pengetahuan yang memadai. Jika pemerintah terus mengabaikan aspirasi masyarakat, gelombang penolakan akan terus berulang.
Poin utama dari demokrasi konstitusional adalah bagaimana komunikasi politik pemerintahan dapat memastikan bahwa penegakan konstitusi dan aspirasi rakyat tidak bisa dipisahkan. Selama masyarakat tidak dilibatkan dalam pembentukan kebijakan, mereka akan terus mencurigai adanya agenda tersembunyi di balik revisi UU TNI, termasuk kekhawatiran tentang kembalinya Dwifungsi ABRI.
Absolutisme yang dipertontonkan oleh pemerintah dan DPR RI merupakan bentuk pengkhianatan terhadap Reformasi. Tidak heran jika muncul anggapan bahwa pemerintahan hari ini adalah "pengkhianat Reformasi" dan bahwa DPR RI telah gagal menjalankan perannya sebagai wakil rakyat. Kini, Reformasi berada di titik nadirnya—kesempatan rakyat untuk menjadi pemegang kedaulatan tertinggi semakin sirna karena tidak ada lagi ruang bagi mereka dalam proses legislasi.
Selamat tinggal, Reformasi. Beristirahatlah dengan tenang.
Oleh : MUHAMAD HADIYAN RASYADI
(WAKIL KETUA BIDANG HUKUM DAN HAM KNPI KABUPATEN CIANJUR)
